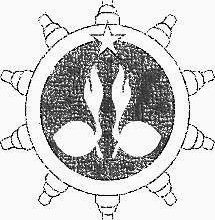Dalam buku Scouting for Boys, Robert Baden Powell menerangkan bahwa istilah kepramukaan (scouting) erat kaitannya dengan aktivitas penjelajahan dan perintisan di alam terbuka yang dikemas dalam bentuk permainan edukatif sesuai minat dan bakat anggotanya.
Secara harfiah, kata scout berarti pengintai. “Scout” awalnya digunakan sebagai sebutan bagi para anggota militer yang diberi tugas untuk memantau atau memata-matai wilayah musuh. Sangat wajar jika Baden Powell menggunakan istilah scout tersebut, mengingat latar belakangnya sebagai perwira militer Inggris. Di bidang olahraga, istilah scout juga digunakan bagi pencari bakat calon pemain baru atau sebagai analis kekuatan dan kelemahan tim lawan.
Dari 176 negara anggota WOSM (organisasi kepramukaan sedunia), lebih dari separuhnya menggunakan “scout” sebagai sebutan untuk “pramuka”. Selebihnya menggunakan penamaan sendiri sesuai bahasa negara masing-masing, tetapi tetap menggunakan terminologi “pengintai” atau “penjelajah”. Contohnya, negara-negara Arab menggunakan kata alkashafat, di negara-negara berbahasa Portugal menggunakan kata escuteiro, dan izvidaca di negara-negara balkan. Begitu pula Malaysia dan Brunei Darussalam yang menggunakan istilah pengakap. Belanda, yang awalnya menggunakan istilah verkenner (penjelajah) dan padvinder (penuntun, pencari jejak), pada tahun 1973 secara resmi sudah memakai istilah scout. Pfadvinder, yang arti dan bunyinya sama dengan padvinder, saat ini hanya digunakan di negara-negara yang berbahasa Jerman (Jerman, Liechtenstein, Austria).
Padvinderij di Indonesia
Di Indonesia, “kepramukaan” sudah dikenal sejak zaman penjajahan dengan nama padvinderij. Pada masa awal perkembangan gerakan kepramukaan (scout movement) ke seluruh dunia, wilayah Indonesia masih berstatus negara koloni yang bernama Hindia Belanda. Saat itu bahasa Indonesia belum menjadi bahasa resmi. Selain bahasa daerah, yang umum digunakan adalah bahasa Belanda dan bahasa Melayu.
Pada tahun 1910 organisasi kepramukaan didirikan di Belanda dengan nama De Jonge Verkenners. Setelahnya, berdiri organisasi lain seperti Nederlandse Padvinders Organisatie (NPO), Eerste Nederlandse Meisjes Gezellen Vereeniging (ENMGV) dan Nederlandse Padvinders Bond (NPB). Salah satu dari organisasi tersebut, NPO, kemudian mendirikan cabangnya di Hindia Belanda pada tahun 1912. Dua tahun kemudian, NPO pusat di Belanda memberikan wewenang pengurus NPO di Hindia Belanda untuk membentuk organisasi sendiri bernama Nederlands Indische Padvinders Vereeniging (NIPV). Anggotanya terdiri dari anak-anak Belanda totok dan peranakan. Hanya sebagian kecil anak-anak pribumi yang punya kesempatan bergabung, itupun hanya dari golongan bangsawan.
Sejak awal 1900-an, pemerintah Belanda memberlakukan politik etis di Hindia Belanda. Salah satu kebijakannya yaitu memperbolehkan masyarakat pribumi mendirikan organisasi sendiri. Di masa itulah lahir bermacam-macam organisasi dan perkumpulan, seperti Budi Utomo yang bercorak pendidikan dan kebudayaan, Indische Partij bercorak politik, dan Sarekat Islam yang bercorak keagamaan dan ekonomi.
Terinspirasi dari aktivitas NIPV, Mangkunegara VII (Adipati Mangkunegaran) mendirikan Javaansche Padvinders Organisatie (JPO) sebagai tempat pembibitan dan latihan ketentaraan Mangkunegaran. JPO adalah organisasi kepramukaan pertama yang didirikan oleh pribumi di nusantara (1916). Karena sifatnya sebagai sarana pendidikan dan pengkaderan bagi anak-anak dan remaja, organisasi-organisasi yang ada ramai-ramai membentuk organisasi padvinderij-nya masing-masing sebagai underbow.
Budi Utomo mendirikan Nationale Padvinderij, Sarekat Islam membentuk Sarekat Islam Afdeling Padvinderij (SIAP). Jong Java mendirikan Jong Java Padvinders (JJP), dan Jong Islamieten Bond dengan Nationale Indonesische Padvinderij (NATIPIJ). Selain padvinder, beberapa organisasi juga menggunakan nama lain, seperti Muhammadiyah yang mendirikan Hizbul Wathan (Pembela Tanah Air) yang sebelumnya bernama Muhammadiyah Padvinderij, serta Taruna Kembang yang dibentuk oleh Kesunanan Surakarta.
Dari Padvinder Menjadi Pandu
Pesatnya pertumbuhan organisasi yang serupa dengan padvinderij membuat pemerintah kolonial Hindia Belanda meminta semua organisasi itu bergabung ke dalam NIPV. Karena permintaan tersebut ditolak oleh padvinder-padvinder non-Belanda, pemerintah kolonial kemudian melarang penggunaan istilah padvinder dan padvinderij bagi organisasi pribumi.
Menanggapi larangan itu, pada kongres SIAP tahun 1928, Haji Agus Salim sebagai pimpinan Sarekat Islam mengusulkan istilah “padvinder” diganti dengan “pandu” (penuntun), dan “padvinderij” diganti “kepanduan”. Agus Salim adalah tokoh pergerakan nasional yang menguasai bahasa Minang dan Melayu, juga fasih berbahasa Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, Arab, Turki, Jepang, Latin, dan Mandarin.
Kata pandu sendiri berasal dari bahasa Melayu yang diserap dari bahasa Sanskerta, yang berarti putih atau pucat. Dalam kisah Mahabharata, Pandu adalah ayah dari para Pandawa. Ia memiliki julukan tersebut karena kulitnya yang putih pucat. Kata Pandu dipilih sebagai gambaran teladan, pembimbing dan penunjuk jalan bagi anak-anaknya ksatria Pandawa. Istilah “pandu” dalam konteks menuntun atau membimbing, berkembang menjadi sifat kepemimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai pendidikan yang ditanamkan bagi anak-anak dan remaja pribumi. Dari situ bisa terlihat kapabilitas Agus Salim dalam memadankan kata padvinder (path finder dalam bahasa Inggris) menjadi pandu dalam bahasa Melayu.
Diawali dari SIAP yang menggunakan kata pandu, berbondong-bondong seluruh organisasi serupa mengubah kata padvinder pada nama organisasinya, seperti Jong Java Padvinderij (JJP) menjadi Pandu Kebangsaan, dan Nationale Indonesische Padvinderij (NATIPIJ) menjadi Pandu Islam Nasional. Istilah padvinder tidak lagi digunakan.
Dari Pandu ke Pramuka
Pertumbuhan organisasi kepanduan terus meningkat. Namun, kondisi Indonesia sejak awal pergerakan kemerdekaan dipenuhi dengan benturan bermacam ideologi. Terdapat tiga ideologi besar pada masa itu, yaitu islamisme, nasionalisme, dan marxisme. Perbedaan ideologi itu pula yang mempengaruhi beragamnya organisasi kepanduan. Sebagaimana dijelaskan tadi, sebagian besar organisasi kepanduan adalah bentukan dari organisasi induk yang bermacam-macam pula ideologinya.
Berangkat dari keadaan itu, para pemimpin pandu terus berusaha untuk mempersatukan organisasi-organisasi kepramukaan dalam satu wadah induk. Berkali-kali penyatuan yang telah disepakati tidak bertahan lama. Pada awalnya telah dibentuk Persaudaraan Antara Pandu Indonesia (PAPI) yang berbentuk federasi (perkumpulan beberapa organisasi). Atas inisiasi dr. Moewardi, dibentuk Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI). KBI tidak lagi berbentuk federasi, tetapi hasil peleburan dari organisasi-organisasi kepanduan. Dalam perjalanannya, organisasi kepanduan lain melebur bersama KBI menjadi Pandu Rakyat Indonesia (PRI). Setelah PRI didirikan, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan bahwa PRI adalah satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia. Namun, karena persoalan perbedaan ideologi, dan keinginan organisasi kepanduan yang lain untuk tetap berdiri sendiri-sendiri, kedudukan PRI sebagai organisasi tunggal ditolak. Pemerintah lantas mencabut keputusan teresebut. Beberapa organisasi kemasyarakatan dan partai politik kembali mengaktifkan organisasi kepanduannya masing-masing.
Meskipun tidak ada lagi organisasi tunggal, tetap dibentuk Ikatan Pandu Indonesia (Ipindo) sebagai federasi kepanduan putra, dan Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia (Poppindo) dan Persatuan Kepanduan Putri Indonesia (PKPI) sebagai federasi kepanduan putri. Selanjutnya Ipindo, Poppindo, dan PKPI dilebur menjadi satu federasi, yaitu Persatuan Kepanduan Indonesia (Perkindo). Jadi, meskipun telah dibentuk organisasi federasi, organisasi kepanduan yang lain tetap menjalankan pendidikan kepanduan sesuai ideologi organisasi induknya.
Di sisi lain, banyaknya organisasi kepanduan yang bermunculan dengan ideologi yang bermacam-macam, menjadi sasaran dari golongan komunis. Mereka menyatakan bahwa kepanduan yang lahir dari gagasan Baden Powel mengandung unsur kapitalisme dan imprealisme. Saat itu golongan komunis juga sedang gencar-gencarnya menyebarkan model pendidikan ala komunis bagi anak-anak dan remaja. Ketika dilaksanakan Pemilu tahun 1955, organisasi kepanduan yang menjadi underbow ormas dan partai politik tampil dengan seragam pandu turut berkampanye politik. Pembinaan pandu banyak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan kepanduan dan lebih mendahulukan kepentingan kelompoknya sendiri-sendiri.
Di tengah kondisi tersebut para pemimpin pandu terus mendorong persatuan antara organisasi kepanduan secara nasional. Selama proses penyatuan organisasi kepanduan, terjadi tarik ulur di antara golongan kepanduan. Di antaranya termasuk penggunaan nama perkumpulan. Presiden Soekarno, yang bertujuan untuk menyatukan organisasi kepanduan di Indonesia, juga menginginkan penggunaan nama baru yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengusulkan istilah “pramuka” kepada Presiden Soekarno.
Kata pramuka berasal dari bahasa jawa, yaitu poromuko. Poromuko bermakna orang-orang yang berada pada barisan terdepan. Dalam bahasa Kannada (mirip bahasa Sanskerta) kata pramuka berarti “yang utama”. Pengusulan istilah pramuka juga dilakukan untuk menyiasati tekanan golongan komunis untuk menggunakan istilah “pionir muda”. Gerakan pionir muda adalah gerakan pendidikan non formal bagi anak-anak dan remaja yang berkembang di negara-negara komunis.
Atas prakarsa Presiden Soekarno, diundanglah tokoh-tokoh dan pemimpin pandu. Dalam pertemuan tersebut, disepakati seluruh organisasi kepanduan melebur menjadi sebuah organisasi tunggal. Diputuskan pula bahwa istilah “pandu” berubah nama menjadi “pramuka”, dan “kepanduan” menjadi “kepramukaan”. Hasil pertemuan itu ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka.
Dari uraian singkat ini, perubahan nama dari pandu menjadi pramuka bukan hanya sekadar pergantian istilah saja. Perubahan itu menjadi simbol persatuan segenap elemen kepanduan-kepramukaan untuk menyamakan arah dan tujuan gerakan demi kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan dan ideologi kelompok-kelompok tertentu.
Penggunaan kata “pramuka”, dan bukannya “scout”, tidak mengecilkan peran Baden Powell sebagai pencetus gerakan ini. Perubahan kata pandu menjadi pramuka juga tidak mengesampingkan peran tokoh-tokoh yang telah merintis kepramukaan di Indonesia, baik ketika masih bernama padvinderij maupun kepanduan. Tulisan yang terbatas ini tidak bermaksud menyederhanakan sejarah panjang kepramukaan di tanah air, tetapi mencoba menelusuri perjalanan identitas sebuah gerakan. Gerakan yang turut serta mewarnai perjuangan mencapai kemerdekaan bangsa, dan terus berusaha mengisi kemerdekaan tersebut dengan karya-karya pembangunan, sesuai dengan tujuan para pendirinya. (Dd)